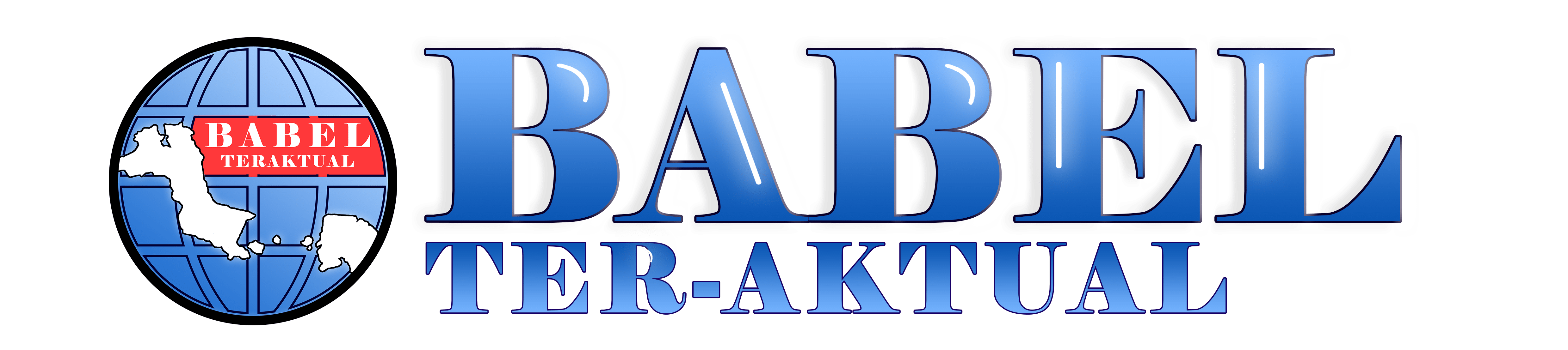Oleh Fakhruddin Halim
Senin, 15 Januari 2024
DENGAN seorang kawan, kami berbicara cukup alot soal inflasi, ditemani: saya memesan secangkir kopi, kawan tadi memesan secangkir lemon tea panas, tapi tidak sebagaimana kopi yang saya kenal ketika masih bersekolah di SD hingga SMU.
Maklum, sebagai anak petani kopi, iya, kopi itu hitam pahit. Ketika SMU tabu rasanya mampir ke kedai kopi. Tua sekali rasanya. Era itu, anak muda iya ke warung bakso atau minum es campur dan sejenisnya.
Ke kedai kopi? Satu dua kali saja, itu pun biasanya karena ikut kakak sepupu ke pasar, mampirlah di kedai kopi.
Pilihannya pun cuma ada dua. Kopi hitam atau kopi susu. Makanan pendampingnya pun tersaji ketan, pisang goreng, ubi goreng, bakwan, mie celor atau jajanan pasar jadul begitulah.
Kembali ke inflasi. Cabai “dikutuk” sebagai salah satu penyebab inflasi yang pedas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Perkara cabai ini tak main-main. Grafiknya bisa naik tajam jika cabai ikutan cawe-cawe. Ya, maklum saja, peminatnya banyak, yang nanam sedikit. Memang kadang banyak, tapi sering pula kapok menanam lagi.
Sebab, pada saat menanam harga tinggi, begitu panen harga anjlok. Padahal, paling tidak, untuk menanam cabai merah keriting atau cabai besar, mulai pengolahan lahan hingga panen butuh biaya paling tidak berkisar Rp15.000 hingga 20.000 per batang. Mulai dari pengolahan lahan, biaya pupuk, pestisida, upah tenaga kerja dan bermacam biaya lainnya.
Bayangkan kalau ketika panen harga Rp20 ribu atau bahkan cuma Rp10 ribuan. Petani rugi. Mau bangkit menanam lagi, modal habis. Secara psikologis pun trauma.
Ketika harga tinggi, petani ramai-ramai menanam. Panen pun nyaris serentak. Over produksi. Sudah menjadi hukum ekonomi, ketika produksi dan permintaan tidak seimbang, apa yang terjadi? Kalau barang banyak, permintaan sedikit: harga turun. Sebaliknya, barang sedikit, permintaan tinggi: harga naik.
Apalagi, penyebab harga bukan saja produksi lokal melimpah, tapi masuk juga cabai dari luar pulau. Yang biaya produksinya untuk sejumlah variabel lebih murah jika dibandingkan dari Babel. Artinya, masih terdapat margin meski tidak begitu besar.
Petani pun tidak siap dengan pasca panen. Padahal sepanjang hidup manusia titik equilibrium sulit atau bahkan tidak pernah terjadi. Selalu saja begitu.
Lalu bagaimana solusinya? Dalam ruang-ruang kelas diskusi yang nyaman, selalu saja kalimat pendek ini diulang: perlu inovasi.
Layaknya kopi, harga di tingkat petani kini mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah perkopian, setidaknya di Indonesia dan setidaknya pula sepanjang ingatan saya.
Nah, pagi ini, Senin, 15 Januari 2024, saya terkejut. Menemani anak makan sahur, dua bungkus kecil cabai kemasan ikut disajikan di piring tahu goreng. Saya pun bertanya, itu apa? Sebab, sepengetahuan saya, Faqih tidak begitu suka makan cabai atau memakan makanan yang terlalu pedas.
“Cabai, ini level pedas 15. Kalau abi mau yang level lebih pedas lagi, ada. Nanti abang belikan. Yang penting ongkosnya ada,” kata putra kami Faqih, tersenyum.
Saya pun balik bertanya, apakah beli dari Jakarta? Karena sepupunya baru sampai dari Jakarta. Barangkali saja ia menitipkannya.
“Tidak, beli di warung. Banyak koq dijual di warung-warung. Rasanya pun gurih dan bermacam rasa, coba aja,” ujarnya.
Saya pun membuka sebungkus, lalu menaburkan ke tahu goreng. Benar saja, rasanya gurih, terasa pedasnya. Tahu pun ludes. Ternyata praktis. Tidak perlu digoreng lagi. Jadi siap saji.
Pertanian, jika tidak dibarengi dengan inovasi akan kolot, kuno, ortodok dan tidak pernah keluar dari lingkaran persoalan yang itu, itu saja.
Kini hilirisasi cabai. Sayangnya, bukan produk Babel, tapi dari luar pulau. Petani tidak perlu khawatir jika hikirisasi berjalan. Produksi cabai akan terserap oleh industri meski baru skala UMKM. Pasar pun terbuka lebar. Bukan saja lokal, tapi bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
Dengan harga yang stabil petani pun bisa konsisten bertanam atau berproduksi. Hilirisasi ini juga kalau diolah sendiri maka akan memberi nilai tambah. Selain itu, membuka peluang bagi generasi millenial untuk terlibat dan masuk ke sektor pertanian. Lapangan pekerjaan terbuka sehingga bisa menyerap tenaga kerja dari kaum millenial.
Kopi, lebih dulu menjadi moderen. Hilirisasi kopi bahkan kini sudah naik level ke industri perkopian.
Lalu, bagaimana hilirisasi pertanian?